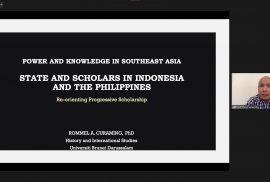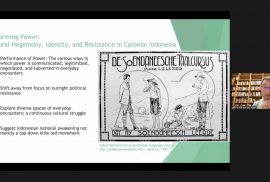Rabu (19-10), Departemen Sejarah UGM menyelenggarakan workshop bertajuk Transnational Histories of Activism in Southeast Asia and Beyond. Bersama dengan Bristol University dan Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan (RUAS), pembicara dari berbagai bidang diundang untuk memberikan kuliah umum mengenai aktivisme transnasional. Pembicara-pembicara yang diundang mencakup Brigitta Isabella, Fadiah Nadwa Fikri, Ita F. Nadia, Su Lin Lewis, Widya Fitrianingsih, Wildan Sena Utama, dan Yulianti. Acara dimulai dengan sambutan dari Abdul Wahid selaku Ketua Departemen Sejarah UGM.
berita
Selasa (20-9), Departemen Sejarah UGM mengadakan kuliah umum berjudul Towards an End of Colonialism: Mid-Century European Photographers Working for an Independent Indonesia. Brian Arnold dari Cornell University menjadi pembicara dalam acara ini, ditemani oleh Satrio Dwicahyo, dosen Departemen Sejarah UGM. Dalam kuliah umum tersebut, Arnold berbicara mengenai kekuatan foto dan para fotografer Eropa yang berpihak kepada Indonesia.
Fotografi seringkali dipandang sebagai cuplikan suatu keadaan pada masa lalu. Dalam arsip maupun buku sejarah, ia bagaikan bukti statis yang netral atas terjadinya sesuatu. Namun, Arnold berargumen bahwa foto lebih kompleks daripada itu. Ia merupakan alat yang manjur untuk mendiseminasi pengetahuan. “Semua hal yang pernah dilalui oleh seorang fotografer memengaruhi caranya mengambil foto,” ujar Arnold. “Apa yang dibingkai di dalam foto sama pentingnya dengan apa yang tidak dibingkai di dalam foto. Semua itu menciptakan sensibilitas subjektif dalam fotografi.” Subjektivitas itu dapat muncul dalam bentuk sehalus latar belakang pemotret yang hanya mengikuti perintah atasan maupun kepentingan yang terinstitusionalisasi.
Pada hari Sabtu, 17 September 2022, Departemen Sejarah UGM menyelenggarakan reuni dan kongres alumni Sejarah FIB UGM bertajuk Merajut Kenang, Merenda Juang. Lagu Cintaku karya Chrisye berdentang di auditorium Gedung Soegondo lantai 7, mengakhiri perbincangan alumni-alumni pada coffee break dan kegiatan jual-beli buku. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars UGM, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh Abdul Wahid selaku Kepala Departemen Sejarah UGM.
Pengenalan kembali Departemen Sejarah UGM seperti acara rutin dan pengurus program Departemen dilakukan oleh Abdul Wahid. Kemudian, para pengunjung disuguhkan penampilan dari berbagai pihak seperti alumni dan mahasiswa Sejarah UGM. Terdapat pertunjukan musik, puisi, tari-tarian, hingga sulap.
Prof. Dr. Marieke Bloembergen dari KITLV/Leiden University dalam kesempatan ini memberikan kuliah umum dengan tajuk The Burden of Colonial Things: Alternative Knowledge Production, Indonesian Perspectives, and the Search for Enlightenment, pada Kamis, 18 Agustus 2022, pukul 10.00-12.00 WIB. Acara ini diselenggarakan oleh Departemen Sejarah UGM dan dipandu oleh Dr. Agus Suwignyo. Perkuliahan ini juga merupakan bagian dari program kerja sama dengan Perkumpulan Program Studi Sejarah Se-Indonesia (PPSI) sehingga diikuti oleh dosen dan mahasiswa dari 12 universitas di Indonesia, yaitu Universitas Airlangga, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Halu Oleo, Universitas Sanata Dharma, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Jember, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Universitas Negeri Semarang. Mahasiswa yang memiliki kelas perkuliahan pada pagi hari wajib mengikuti perkuliahan ini sebagai gantinya.
Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM menggelar workshop yang mendatangkan seorang profesor sekaligus peneliti dari Belanda bernama Fridus Steijlen. Kegiatan yang bertajuk “Meniti Arti: Cerita-Cerita dari Sumber” ini dilaksanakan secara luring di lantai 3 Gedung Soegondo, Fakultas Ilmu Budaya UGM, pada 14 Juni 2022, pukul 10:00-12:00 WIB. Workshop ini peserta dari mahasiswa maupun umum.
Fridus Steijlen memulai presentasinya dengan memperkenalkan diri dan bercerita mengenai pengalamannya mendengar kisah dari dua sudut pandang, yakni orang-orang Belanda dan orang-orang Indonesia tentang sejarah Indonesia periode 1945-1949. Fridus telah melakukan banyak wawancara dan menjumpai banyak veteran. Salah satu pengalaman unik yang dibagikan Fridus adalah ia pernah melakukan wawancara dengan salah satu veteran dari Delanggu, Klaten, yang beberapa tahun kemudian, ia tidak sengaja bertemu dengan cucu dari veteran tersebut. Setelah Fridus selesai menyampaikan materi, ia membuka sesi diskusi interaktif dengan peserta.
Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM menggelar kegiatan workshop dari pembicara seorang fotografer profesional dari Belanda bernama Isabelle Boon. Kegiatan ini diadakan secara luring pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 09.30 – 12.30 yang diikuti oleh mahasiswa dan umum namun kuotanya terbatas. Kegiatan workshop luring ini diadakan di Gedung Soegondo, Fakultas Ilmu Budaya UGM. Workshop ini dipandu oleh Isabele sendiri dan suaminya yang mendokumentasikan acara yang sedang berlangsung.
Kegiatan dimulai dengan Isabelle yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang fotografer dan menceritakan perjalanannya dalam menelusuri jejak sang tokoh nasional Indonesia Sutan Sjahrir. Isabelle menggunakan fotografi untuk menelusuri jejak tokoh nasional Sutan Sjahrir di Indonesia dan Belanda. Di Indonesia, Isabelle telah mengunjungi Jakarta, Bandung, Banda, Linggarjati dan Yogyakarta untuk melacak jejak sang tokoh nasional Indonesia. Isabelle juga menunjukkan bahwa dia telah melakukan pameran mengenai dokumentasi foto dan video yang telah dia abadikan selama proses melacak jejak Sutan Sjahrir dengan anak-anak dan warga di pulau Banda. Selama workshop berlangsung, mahasiswa dan/atau akademisi mendiskusikan tema warisan Sjahrir seperti pendidikan, kebebasan, kesetaraan, tetapi juga untuk berbagi ide dan pendapat mereka tentang tema-tema tersebut. Dengan menggunakan alat Mentimeter dan kahoot, workshop bersifat interaktif. Peserta diminta dari kelompok kecil untuk diskusi lebih mendalam menggunakan permainan kartu koneksi untuk beberapa pertanyaan yang relevan dengan tema workshop pada hari ini.
Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM menggelar kegiatan Screening Film dengan judul kegiatan “Refleksi 24 Tahun Reformasi Melalui Film Pendek Sejarah Indonesia Kontemporer”. Kegiatan yang diadakan ini berlangsung secara daring melalui zoom dengan partisipan mahasiswa S1 Sejarah dan lainnya. Screening Film ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 10.00-12.00 WIB. Dalam kegiatan ini mengundang pembicara Dr. Agus Suwignyo, M.A selaku Dosen S1 Sejarah dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer dan pembicara lainnya seorang Founder The Visual Storyteller, Satria Setya Adhi Wibawa.
Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM menggelar kegiatan sosialisasi dan berbagi pengalaman program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan secara daring melalui zoom dengan mahasiswa S1 Sejarah. Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu, 25 Mei 2022 pukul 10.00 – 12.00 WIB yang dipandu oleh Satrio Dwicahyo, M.A dari Staf Pengajar S1 Sejarah. Dalam kegiatan ini juga mengundang beberapa pembicara diantaranya Dr. Mutiah Amini selaku Ketua Program Studi S1 Sejarah UGM, Zahra Aulia sebagai Peserta Program IISMA ke Humboldt-Universitat zu Berlin, Lesta Alfatiana sebagai Alumnus Program Kampus Merdeka Bank Indonesia dan M. Rozzaq sebagai Alumnus Program Studi Kolaborasi dengan ISI Yogyakarta.
Departemen Sejarah FIB UGM mengadakan sebuah rangkaian diskusi daring dan bedah buku bersama Rommel Curaming, Ph.D., dari Universiti Brunei Darussalam. Rangkaian acara diskusi daring dan bedah buku dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada hari Rabu dan Kamis, 8-9 Desember 2021. Kedua rangkaian acara ini diselenggarakan melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube Departemen Sejarah UGM.
Diskusi daring dilaksanakan pada pukul 16.00 sampai 17.30 WIB. Diskusi daring dibuka oleh Satrio Dwicahyo selaku perwakilan dari Departemen Sejarah UGM dan selanjutnya diambil alih oleh Yuanita Wahyu Pratiwi sebagai moderator. Setelah itu, Rommel Curaming memulai diskusi dengan melakukan presentasi. Budiawan, Ph.D, dosen senior di Kajian Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada juga turut menjadi pembahas dalam diskusi seri pertama ini.
Pada Kamis (18/11) kemarin, Departemen Sejarah UGM kedatangan tamu seorang sejarawan dari Colby College USA, Dr. Arnout Van der Meer. Kali ini, Dr. Arnout secara virtual hadir dalam acara yang bertajuk Diskusi Buku Performing Power: Cultural Hegemony, Identity, and Resistance in Colonial Indonesia. Di acara yang diadakan via zoom meeting sekaligus disiarkan langsung di kanal YouTube Departemen Sejarah UGM ini, Dr. Arnout sebagai penulis buku ditemani Dr. Sri Margana sebagai pembahasnya. Selain itu, acara yang dipandu oleh Wildan Sena Utama ini dimulai pada pukul 09.00 WIB dan diikuti oleh sekitar 80 peserta dari civitas akademik maupun umum.